Oleh : Slamet Luwihono
Pendahuluan
Bukan upaya yang mudah untuk memberikan gambaran tentang desa dan kota secara utuh, disamping karena kompleksitas permasalahan yang ada di desa maupun di kota juga karena sifat dinamis desa dan kota sebagai akibat pembangunan. Gambaran yang diberikan sekarang tentang desa atau kota belum tentu relevan untuk kondisi dua tahun mendatang. Dengan demikian pembahasan tentang desa seringkali tidak dapat dilepaskan dari terjadinya perubahan sosial desa yang demikian cepat. Rogers dalam bukunya Social Change in Rural Societies: An Introduction to Rural Sociology, memandang perubahan sosial sebagai suatu proses yang melahirkan perubahan-perubahan di dalam struktur dan fungsi dari suatu sistem kemasyarakatan.[1] Perkembangan yang cepat tersebut tentunya tidak lepas dari perkembangan teknologi pertanian dan juga perubahan struktur perekonomian dan politik. Perubahan sistem produksi telah membawa perubahan yang mendasar pada system pertanian yang pada gilirannya berdampak pada perubahan kehidupan masyarakat pedesaan sebagai petani atau menggantungkan hidupnya pada pertanian di pedesaan.
Secara sosiologis, Maschab menggambarkan desa sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan di mana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam. Lebih jauh lagi Maschab menyebukan bahwa desa diasosiasikan dengan satu masyarakat yang hidu sederhana, pada umumnya hidup dari lapangna pertanian, ikatan sosial, adat dan tradisis masih kuat, sifat jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif masih rendah dan sebagainya.[2] Dalam perkembangannya, sebagai akibat dari arus modernisasi sebagian desa telah mengalami perubahan secara drastis dan jauh dari kondisi-kondisi yang banyak digambarkan oleh para ahli. Modernisasi sebagai satu pendekatan pembangunan telah juga membawa perubahan sosio-kultur desa. Dalam konteks yang demikian, desa tidak lagi bisa didefinisikan sebagai tempat tempat tertentu yang masih jujur dan bersahaja, lugu dan masih menjalin ikatan-ikatan sosial secara informal. Meskipun demikian, dalam kenyataannya dampak modernisasi terhadap masyarakat desa memang tidak dapat digeneralisir. Secara nyata masih ada masyarakat desa yang masih hidup mematuhi tradisi dan adat istiadat turun temurun, dan banyak diantaranya dalam kondisi tidak maju atau terbelakang menurut ukuran modernitas. Desa di Badui dalam atau pada umumnya desa-desa di luar Jawa misalnya merupakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi kepercayaan tradisional dan adat sehingga derasnya arus modernisasi tidak mampu mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sebagian desa lagi, terutama desa-desa di luar Jawa, secara geografis terletak sangat jauh dari dunia modern sehingga sulit untuk dijangkau dan akibatnya tidak mudah untuk dipengaruhi.[3]
Pada masa lampau penduduk pedesaan pada umumnya hidup dengan sistem subsisten, tetapi paradigma modernisasi telah mengubah mode of production dari tidak berorientasi keuntungan ke berorientasi pada keuntungan. Dengan perkembangan-perkembangan yang ada di pedesaan dalam kenyataannya untuk kasus-kasus desa tertentu terutama di Jawa dari karakteristik dan fisik menjadi sulit membedakan antara desa dengan kota. Perbedaan-perbedaan desa-kota sangat tepat dinilai dengan indikator yang mengukur kesejahteraan secara langsung. Demikian juga kesehatan dan hidup mengandung nilai universal dengan demikian memberikan ukuran yang mengandung validitas lintas - kultural.[4] Indikator kesejahteraan ini lebih dimaknai sebagai kesejahteraan secara ekonomi. Kota dipandang lebih sejahtera daripada desa yang tidak sejahtera dari ukuran ekonomi. Pemaknaan yang demikian ternyata berdampak terhadap cara pandang orang desa terhadap keadaan kota yang digambarkan sebagai menjanjikan ketersediaan sumber-sumber ekonomi untuk kesejahtreraan. Sementara itu desa dipandang sebagai tempat yang sulit sebagai tempat untuk meningkatkan kesejahteraan. Terlepas dari tingkat kebenaran cara pandang tersebut, cara pandang dari sisi kesejahteraan ini telah menjadi salah satu pendorong orang-orang desa berpindah (melakukan urban) ke kota dalam rangka untuk meningkatkan sumber penghasilan.
Fenomena boro menjadi upaya yang sering ditempuh oleh masyarakat desa yang merasa kesulitan meningkatkan kesejahteraan ekonominya untuk pergi ke kota. Boro menjadi upaya alternatif bagi masyarakat desa untuk mencari pekerjaan ke kota karena tertutupnya peluang mencari pekerjaan di desa yang dipandang tidak dapat menjanjikan. Meskipun boro mengandung resiko-resiko sosial, psikologi, ekonomi dan lain-lain, kesenjangan kesejahteraan desa-kota yang begitu drastis lebih menyingkirkan pertimbangan-pertimbangan atas dasar resiko-resiko tersebut. Apa peranan yang diberikan oleh kaum boro terhadap kehidupan sosial di desa asalnya dan bagaimana kehidupan kaum boro dalam menjalani kehidupan di kota yang sangat jauh berbeda dengan kehidupan sosial di desa asalnya ? Permasalahan-permasalahan tersebut yang akan menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini.
Kaum Boro dan Peranannya Dalam Kehidupan Sosial Desa
Pengertian boro dalam konteks ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengertian migrasi musiman seperti yang dikemukakan oleh Alan Gilbert & Josef Gugler. Gilbert dan Gugler[5] mendeskripsikan migrasi musiman sebagai berikut:
| "Pemisahan keluarga seringkali menciptakan bentuk migrasi musiman. Setelah masa kerja yang mungkin berakhir 6 bulan atau 2 tahun, migran tersebut kembali lagi untuk bermukim dengan keluarga besar mereka. dalam kasus yang ideal , kepulangan kaum migran bersamaan dengan kebutuhan akan tenaga kerja di sawah atau ladang di desa. Di beberapa tempat, kaum migran menjadi tenaga kerja kontrakan , misalnya, tenaga mereka digunakan dalam masa yang telah ditentukan dan disediakan biaya transport untuk pulang pergi. Berulangnya perpindahan musiman ini umum sifatnya, sehingga banyak kaum migran yang bertambah luas pengalaman kotanya. Upaya spekulasi migrasi musiman merupakan respon awal "masyarakat tradisional" terhadap peluang-peluang baru untuk mendapatkan upah dan barang manufaktur, untuk menunjukkan kepada "orang-orang primitif" yang sedang membuat barang pintas untuk masuk ke dalam suatu lingkungan yang asing." |
Dari deskripsi tentang migrasi musiman tersebut, kaum boro dapat digunakan untuk menunjuk sekelompok orang desa yang pergi merantau ke kota untuk mencari pekerjaan. Biasanya masyarakat desa terutama di Jawa, menyebut kaum boro dengan sebutan wong boro. Pada umumnya wong boro ini tinggal di kota selama lebih kurang tiga hingga enam bulan untuk bekerja mengumpulkan penghasilan, selanjutnya mereka pulang kembali ke desanya untuk menjenguk keluarga dan atau tidak pulang tetapi mengirim penghasilan yang mereka peroleh selama bekerja di kota. Setelah pulang di desa asalanya selama kurang lebih satu bulan mereka kembali ke kota untuk bekerja. Tidak jarang juga kaum boro ini pulang ketika musim tanam telah tiba, karean tenaga mereka dibutuhkan selama musim tanam di desa tersebut. Setelah musim tanam selesai, kaum boro ini kembali ke kota sedangkan yang merawat tanaman adalah anggota keluarga yang tinggal di desa. Biasanya dalam melakukan boro, kaum boro tidak mengajak keluarganya (suami dan anak-anaknya). Dengan demikian boro merupakan adaptasi terhadap pemisahan keluarga: boro sebagai bentuk migran yang pulang secara teratur kepada keluarganya dalam jangka waktu yang lama dan dia tetap aktif terlibat dalam permasalahan keluarga besar, dan urusan desanya (lihat, Alan Gilbert & Josef Gugler, 1996: 76).
Determinan perilaku migrasi ini bisa dianalisis dalam beberapa kerangka sistem antara lain:[6]
1. Sistem preferensi, menggambarkan ketertarikan relatif pada berbagai tempat sebagai tujuan dari para pelaku migrasi potensial. Suatu daya tarik wilayah merupakan perimbangan antara nilai-nilai positif dan negatif yang ditawarkan wilayah tersebut. Diantara nilai-nilai positif yang paling penting adalah prospek pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik dari pada di desa tempat asalnya. Namun, boro ini juga berdampak pada nilai-nilai negatif berupa gangguan terhadap hubungan interpersonal denga kerabat dan teman-teman di desa serta kebutuhan untuk mempelajari adat istiadat baru di desa asal.
2. Sistem harga, menjelaskan biaya-biaya berupa uang, energi dan waktu yang digunakan untuk melakukan boro ini.
3. Total sumber daya, yang tersedia untuk semua tujuan juga mempengaruhi keputusan untuk melakukan boro ini.
Disamping determinan-determinan tersebut, boro juga menimbulkan dampak sebagai berikut:
1. Dapat meningkatkan penghasilan bagi kaum boro. Bersamaan dengan konskuensi positif ini terdapat konskuensi lain bernilai negatif bagi pembangunan masyarakat desa berupa kerugian di bidang investasi karena investasi yang semula dimaksudjkan untuk menyelenggarakan dan memberi pendidikan pada anak-anak tetapi pada akhirnya setelah dewasa mereka membaktikan dirinya di tempat lain karena desa dipandang tidak menjanjikan dari sisi materi.
2. Boro dapat mengurangi (meskipun kadang kurang signifikan) ketidakseimbangan/kesenjangan pendapatan antara kota - desa. Ini bisa terjadi karena kaum boro cenderung bergerak dari wilayah berpendapatan rendah (desa) ke wilayah berpendapatan tinggi (kota).
Dari sisi perilaku sosial, kehidupan kota yang meskipun dijalani secara singkat telah dapat merubah pola kehidupan desa. Begitu kaum boro sampai di kota ia dituntut untuk beradaptasi perilaku yang memungkinkan ia mencapai keberhasilan ekonomi secara efektif. Kaum boro yang datang dalam jangka waktu yang singkatpun tidak lagi sepenuhnya bersikap seperti orang desa. Meskipun mereka pada tahap-tahap awal kedatangan ke kota mampu mempertahankan pola dan gaya kehidupan desa dan mampu memegang nilai-nilai desanya tetapi desakan/tuntutan untuk menyesuaikan dengan kehidupan kota sangat kuat sehingga nilai-nilai, gaya hidup dan pola kehidupan desa tergeser. Pertimbangan utama pergeseran nilai, gaya dan pola hidup lebih didominasi oleh pertimbangan adanya kesempatan memperoleh peningkatan ekonomi. Komitmen yang dimiliki kebanyakan kaum boro terhadap komunitas asal dapat menjadikan untuk tidak menjalani kehidupan kota di kota secara penuh.
Investasi sosial sering juga dilakukan oleh kaum boro berupa pengiriman uang ke keluarga mereka, membantu famili untuk mengikuti pendidikan di kota. Semua itu dilakukan seringkali bukan atas dasar kerelaan untuk berinvestasi mengembangkan desanya tetapi di balik semua itu tersembunyi kepentingan yaitu untuk menjaga kepentingan-kepentingan mereka di desa asalnya. Dalam benak mereka tidak ada keinginan untuk selamanya bermukim di kota dan suatu waktu akan kembali ke desa asalnya.
Diantara kaum boro dalam satu kota biasanya terjalin ikatan yang kuat dan komunikasi selalu dijaga. Misalnya orang boro yang baru pulang ke kampungnya (biasanya kepulangan ke kampung tidak dilakukan secara bersamaan) sering membawa informasi dari desa asalnya untuk disampaikan ke orang boro lainnya sehingga orang-orang boro tidak ketinggalan perkembangan informasi di desanya. Mereka selalu mendapat informasi jika ada orang yang mempunyai iakatan keluarga di desanya sedang sakit, tetangganya yang hendak mempunyai hajatan (pesta perkawinan, misalnya), tentang pembangunan yang yang hendak dilaksanakan di desanya bahkan tentang dinamika politik lokal didesanya seperti pemeilihan kepala desa atau kepala dusun. Orang boro yang pulang seringkali dijadikan sarana/media informasi yang mempunyai peranan strategis bagi kaum boro dalam rangka tetap menjalin hubungan-hubungan sosial di desanya.
Peran Kaum Boro Dalam Pembangunan Desa
Dari sisi ekonomi kaum boro dipandang lebih mempunyai kekuatan finansial yang riil dari pada orang desa yang tetap tinggal dan bekerja sebagai petani di desa. Karena pendangan yang demikian kaum boro seringkali menjadi sasaran mobilisasi bagi pembangunan fisik di desa. Peranan kaum boro dalam pembangunan desa ini dideskripsikan oleh Dwi Wuryaningsih sebagai berikut:[7]
| "Pembangunan terbesar yang dilakukan di Desa Kedungringin adalah jembatan Sungai Serang. Pembangunan jembatan sungai serang yang kono menghabiskan dana ratusan juta rupiah didukung oleh seluruh warga desa baik ulama, warga setempat maupun orang-orang boro......... Pada hari lebaran banyak orang-orang boro yang pulang ke kampung. Matdarto (cat. Ketua Kaum boro Kedungringin di Jakarta) mengumpulkan orang-orang boro itu di rumahnya. Dalam pertemuan itu Matdarto menyampaikan gagasannnya untyuk merenovasi Masdjid di Dusun Krajan. Gagasan itu disambut baik oleh orang-orang boro. Untuk merealisasikan gasgasan tersebut, Matdarto, mengadakan pertemuan bagi orang-orang boro setelah mereka sampai di Jakarta untuk mengumpulkan sumbangan dari orang-orang boro. Demikian juga yang disampaikan oleh Matharto, pengurus kaum boro di Jakarta dari dusun Krenceng, Desa Kedungringan bahwa pembangunan di dusunnya banyak mendapat sumbangan dari kaum boro. Ditambahkan pula oleh Matharto jika ide pembangunan di dusunnya datang dari Pak kadus, jalannya pemabngunan itu seringkali menemui kendala. Karean Pak kadus hanya sebatas mempunyai ide saja sedangkan dana masih harus mencari dari sumbangan warga yang belum tentu setuju dengan gagasan Pak kadus. Berbeda jika ide pembangunan datang dari orang-orang boro. Selain ide, orang boro juga mempunyai dana untuk membiayai pembangunan itu" |
Selain kekuatan finansial secara riil yang dimiliki oleh kaum boro yang dapat menunjang pembangunan fisik di desa seperti dupaparkan dalam hasil penelitian di atas, ternya kaum boro juga mempunyai kekuatan politik yang dapat mempengaruhi dinamika [politik lokal di pedesaaan sebagaimana dipaparkan di bawah ini:[8]
| "Terpilihnya Hadi Nurdin sebagai kades, tidak terlepas dari peran kaum boro. Semenjak orang-orang boro di Jakarta mendengar bahwa Hadi Nurdin hendak maju sebagai calon Kades, mereka menyatakan kesanggupannya untuk mendukung Hadi Nurdin. Hubungan yang terjalin dengan baik antara hadi Nurdin dengan orang-orang boro telah melatarbelakangi dukungan orang-orang boro dalam pencalonnanya. Ketika Hadi Nurdin kuliah di IKIP Negeri Jakarta dan tinggal bersama kakaknya, ia cukup dekat dengan orang-orang boro. Seringkali orang boro yang mendapat kesulitan, datang kepada Hadi Nurdin untuk meminta bantuannya. Hal inilah yang menjadikan munculnya kedekatan orang-orang boro dengan Hadi Nurdin." |
Dari kedua paparan tersebut di atas dapat diketahui bahwa pandangan orang desa yang masih tetap tinggal dan bekerja di desa terhadap orang-orang boro adalah didominasi pandangan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan. Dalam kenyataannya memang tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat pendapatan kaum boro dapat dikatakan lebih baik daripada orang-orang yang tetap tinggal di desa. Karena pandangan yang demikian tersebut maka kaum boro seringkali dijadikan tumpuan untuk meminta bantuan baik bantuan yang bersifat individual maupun yang bersifat untuk kepentingan masyarakat desa seperti pembangunan tadi. Selain sebagai tempat meminta dukungan finansial, kaum boro ternyata juga dijadikan tempat memobilisai masa untuk pencarian dukungan politik seperti dukungan dalam pencalonan Kades. Dukungan politik dalam pencalonan kadesa ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari adanya kemmapuan finansial yang dimiliki kaum boro mengingat pencalonan kades seringkali tidak dapat dilepaskan dari money politic. Diharapkan selain dukungan suara memang dukungan uang juga bisa diberikan oleh kaum boro ini.
Penutup
Kesenjangan tingkat kesejahteraan antara desa dengan kota telah menjadi faktor pendorong terjadinya boro ini. Dari sisi ekonomi, kota yang dipandang lebih sejahtera daripada desa telah mendorong orang desa untuk melakukan boro ke kota untuk meningkatkan kesejahtraannya. Pabrik modern dan peluang adanya lapangan kerja di kota telah menanamkan harapan baru bagi masyarakat desa untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya. Alasan ekonomi menjadi alasan yang dominan terjadi arus boro dari desa ke kota. Ini ditunjukkan dengan adanya fenomena boro dari wilayah yang tingkat kesejahteraan ekonomi rendah ke wilayah yang mempunyai tingkat kesejahteraan tinggi.
Bagi masyarakat desa fenomena boro telah membawa dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Bersifat positif karena secara fisik dapat membantu pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pendidikan dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya proses pemaksaan perilaku kehidupan kota di desa yang seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di desa. Terlepas dari dampak yang ditimbulkannya, fenomena boro merupakan dampak dari penerapan pembangunan dengan pendekatan/paradigma pertumbuhan yang berpusat pada kota-kota besar. Karena pertumbuhan dirasa tidak dapat menetes ke wilayah pedesaan maka orang-orang desalah yang harus menjemput pembagian hasil pembangunan dengan datang ke kota. Dengan cara demikianlah hasil pembangunan dapat didistribusikan ke wilayah-wilayah desa.§
Daftar Pustaka
1. Alan Gilberrt dan Josef Gugler, 1996, Urbanisasi dan Kemiskinan Di Dunia Ketiga, Tiara wacana, Jogyakarta.
2. A. Surjadi, 1995, Pembangunan Masyarakat Desa, Mandar Maju, Bandung,
3. Bahreit T. Sugihen, 1997, Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar), RajaGrafindo Persada, Jakarta,
4. C. Dwi Wuryaningsih, 2001, Kiprah Kaum Boro Dalam Kehidupan Masyarakat Desa: Studi Tentang Kaum Boro Di Desa Kedungringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semrang, Makalah disajikan pada Seminar Dinamika Politik Lokal P3PL-Petrcik, di Bandungan, tanggal 26 Juni 2001.
5. Machievelli, 2002, Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, edisi kedua,
6. Suhartono, 2001, Politik Lokal Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
*******
[1] Bahreit T. Sugihen, 1997, Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar), RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 55).
[2] Lihat Suhartono, 2001, Politik Lokal Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, hal. 17-18.
[3] Lihat juga A. Surjadi, 1995, Pembangunan Masyarakat Desa, Mandar Maju, Bandung, hal. 5.
[4] Alan Gilberrt dan Josef Gugler, 1996, Urbanisasi dan Kemiskinan Di Dunia Ketiga, Tiara wacana, Jogyakarta, h. 58.
[5] Alan Gilbert & Josef Gugler,1996, Urbanisasi dan Kemiskinan Di Dunia Ke Tiga, Tiara Wacana Jogja, Yogyakarta, hal. 76.
[6] Machievelli, 2002, Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, edisi kedua, hal 662.
[7] C. Dwi Wuryaningsih, 2001, Kiprah Kaum Boro Dalam Kehidupan Masyarakat Desa: Studi Tentang Kaum Boro Di Desa Kedungringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semrang, Makalah disajikan pada Seminar Dinamika Politik Lokal P3PL-Percik, di Bandungan, tanggal 26 Juni 2001.
[8] Ibid
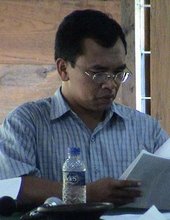


Tidak ada komentar:
Posting Komentar